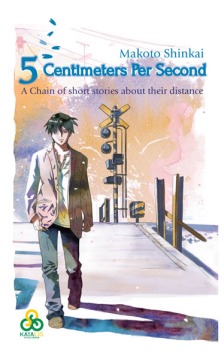Novel ini menjadi novel Italia pertama yang saya miliki. Selama ini koleksi saya hanya novel Indonesia, Jepang, Korea Selatan dan Amerika. Novel ini sungguh istimewa bagi saya. Terlepas dari isinya yang juga istimewa, pertemuan dengan novel ini pun istimewa 🙂
Jika diartikan ke dalam bahasa inggris, novel fiksi ini berjudul ‘White As Milk, Red As Blood‘. Putih seperti susu, merah seperti darah. Sangat menarik judul yang tertulis di covernya. Saya tidak tahu apa-apa mengenai buku ini. Feeling saya mengatakan novel ini layak dibeli karena terdapat label ‘Telah diterjemahkan ke dalam 20 Bahasa’. Untuk kategori sebuah novel fiksi, bisa diterjemahkan dalam 5 bahasa sungguh bagus. Apalagi 20 bahasa. Hal itu menandakan bahwa bobot novel fiksi ini perlu dicermati. Hal tersebut yang membuat saya tidak ragu untuk membawanya pulang dari rak toko buku.
Alessandro D’Avenia adalah penulisnya. Pria Italia bermata biru yang memiliki rambut ikal nan seksi. Untuk profil selengkapnya mengenai Alessandro tidak saya ketahui karena bahasa Italia, jujur, yang tidak saya mengerti. Walaupun google translate ada tetapi tindakan yang melelahkan hanya ingin ‘kepo’ tentang penulisnya. Alessandro menerbitkan novel ini tahun 2010, dan baru 2015 bisa diterbitkan di Indonesia.
Novel ini -menurut saya- bisa dinikmati oleh usia 12 tahun ke atas. Isinya sangat mudah dipahami, walaupun mungkin kita sedikit akan diajak berfilsafat ria, namun menurut saya bisa kita pahami secara perlahan. Tidak mengandung hal berbau vulgar. Cocok untuk usia remaja, malah sangat dianjurkan.
Leonardo, sebut saja ia dengan Leo. Remaja lelaki yang berusia 16 tahun. Leo seperti remaja lain pada umumnya. Membenci sekolah, karena ia pikir sekolah berisi dengan sekumpulan vampir yang siap untuk menghisap darah dari siswa-siswanya. Hal itu hanya bayangan Leo semata yang memandang sekolah adalah tempat yang, sangat, tidak menyenangkan. Penulis sangat piawai menggambarkan karakter Leo sebagai remaja yang bisa dikatakan ‘ababil’ dalam pencarian ‘identitasnya’. Memang tidak jauh berbeda dengan yang dialami semua orang pada saat menginjak remaja. Menentukan diri sendiri untuk dibawa kemana kelak tidak terelakkan lagi bagi seusia Leo. Namun Leo masa bodoh terhadap semua itu. Ia hanya senang nongkrong dengan teman-temannya, bermain musik untuk hiburan, kebut-kebutan dengan motor satu-satunya, dan bermain sepak bola.
Leo bukanlah anak pintar. Bukan berarti bahwa ia bodoh. Tidak juga. Semacam orang yang belum mengerti siapa dirinya sendiri. Tidak ada semangat atau tepatnya tidak memiliki impian. Dan hal tersebut berubah ketika kelasnya mendapat guru filsafat pengganti yang baru. Leo menjulukinya ‘si pemimpi’. Dia berbeda dengan guru-guru lainnya. Leo sangat ‘amat’ tidak suka kepada guru tersebut. Kalian tahukan, benci itu memiliki batas yang amat tipis dengan cinta. Dan kita bisa menebaknya saat awal perkenalan Leo dan si pemimpi yang berujung pada akhir yang bagaimana. Tetapi, penulis tidak menyorot si pemimpi ini terlalu banyak dan terlalu sedikit. Penulis tidak berniat menjadikan si pemimpi sebagai tokoh penting kedua. Hal itu nampak jika kalian membacanya sampai akhir. Si pemimpi hanya muncul pada momen yang dirasa memang seharusnya muncul, seperti di kelas mata pelajarannya. Dia tidak muncul tiap kali ketika Leo harus mengahadapi berbagai kerumitan hidupnya. Disinilah saya suka dengan Alessandro dalam cara berceritanya.
Kenapa si pemimpi dijuluki Leo seperti itu? Hal itu tidak terlepas dari gaya mengajar si pemimpi dalam menjelaskan pelajarannya. Dia banyak memberi tugas tetapi tidak dimasukkan dalam nilai. Dia suka bercerita dan ceritanya membuat seisi kelas terdiam untuk menyimak. Dia seringkali menyebut tentang impian. Inilah yang membuat Leo tidak menyukainya. Karena Leo sendiri tidak tau apa impiannya. Sampai ia sadar bahwa impiannya adalah ‘rambut merah’. Sampai pada akhirnya Leo tahu bahwa ‘rambut merah’ tidak akan selalu ada di dunia. Bagaimana ia akan melanjutkan impiannya walaupun teman dekatnya, Silvi, selalu ada didekatnya.
Hidup terus saja berjalan maju dan memainkan lagunya, tak peduli kau suka atau tidak. Kau hanya bisa menaikkan dan menurunkan volumenya.
Penuturan-penuturan Alessandro dalam balutan kalimatnya mengajak kita untuk tetap diam dengan tenang dan mendengarkan apa yang disampaikannya dalam lembaran putih. Menggunakan alur maju dalam tiap tulisannya membuat kita seolah mengikuti setiap jejak langkah Leo dalam melewati usia 16 tahunnya. Novel ini tidak akan berakhir dengan Leo yang dewasa. Alessandro tidak mau mengajak kita melompati waktu yang sangat jauh ke depan. Cukup hanya rentang usia 16 dan menuju 17 tahun dari tokoh utamanya, Leo. Alessandro tidak lupa menampilkan kehidupan Leo di rumah. Bagaimana hubungannya dengan orangtuanya. Serta perkenalan Leo tentang ‘cinta’.
Saya paham kenapa novel ini patut diperhitungkan untuk menjadi novel terbaik (sebenarnya sudah masuk ke dalam kategori tersebut). Bagi kita yang telah dewasa atau bagi pembaca usia 30an keatas, tidak akan merugi bila mengikuti kisah Leo. Kita semacam belajar lagi untuk menghadapi bagaimana bila kita berhadapan dengan orang seusia Leo. Entah itu adik, keluarga, murid atau anak kita kelak. Hanya satu yang membuat saya tidak nyaman saat membaca novel terjemahannya. Saya masih merasa masih kurang puas pada hasil terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia. Saya tidak tahu tepatnya dimana, tetapi ketika menamatkan semua isinya, saya masih menemukan, tidak sedikit, bahasa yang kurang tepat. Walaupun saya sendiri tidak ahli menerjemahkan, tapi saya cukup lihai untuk memperhatikan tulisannya.
Kehidupan ini memang selalu menenun sebuah pakaian dengan banyak warna buatmu, yang harus dibayarnya dengan malam – malam tanpa memejamkan mata, malam – malam yang sarat dengan sisa – sisa kehidupan – kehidupan lainnya, yang dijalin lagi bersama – sama.